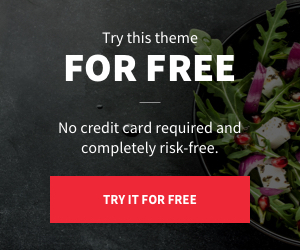Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi kejahatan serius di Asia Tenggara. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang baru usai mengeluarkan deklarasi penting terkait isu ini. Namun, akademisi menilai tanpa tindak lanjut, deklarasi itu tidak bermakna.
Direktur Eksekutif ASEAN Studies Centre, Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Dafri Agussalim memberi apresiasi keluarnya deklrasi tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi, dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, 10-11 Mei lalu. Namun, dia mengingatkan, sebuah kesepakatan tidak akan bermanfaat tanpa tindak lanjut yang tepat.
“Tapi ini kan deklarasi ya, jadi dia tidak atau belum mengikat secara hukum, secara ketat. Itu baru komitmen dan itu bukan hal yang satu-satunya,” kata Dafri, dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Senin (15/5).
Deklarasi itu sendiri merupakan sari dari sedikitnya 10 dokumen yang dihasilkan KTT tersebut.
Dafri menyebut, deklarasi TPPO ASEAN bukan satu-satunya, karena sejak lama organisasi ini berkali-kali mengeluarkan dokumen serupa. Dia memberi contoh, ada deklarasi perlindungan terhadap pekerja migran yang disepakati pada tahun 2007 dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Namun, sampai saat ini tidak ada hasil berarti dari kesepakatan itu.
“Tahun 1979, ASEAN pernah mendeklarasikan ASEAN Drug Free. Ternyata tetap saja sampai sekarang drug trafficking itu berkembang pesat ya di Asia, dan Indonesia lagi-lagi sebagai korban,” beber Dafri.
Deklarasi TPPO ASEAN berisi kesepakatan untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi pemberantasan perdagangan manusia. Caranya dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga terkait, di masing-masing negara anggota untuk menyelidiki dan mengumpulkan data dan bukti.
Kesepakatan lain adalah peningkatan kapasitas hukum untuk mengidentifikasi korban, mendeteksi, dan mengadili kejahatan, melakukan latihan dan operasi terkoordinasi bersama, serta penyelidikan bersama terkait TPPO dan kejahatan transnasional lainnya. Pejabat-pejabat teknis akan berperan besar, seperti kepolisian, imigrasi, unit kejahatan siber dan lainnya.
Karena pengalaman itulah, Dafri mendesak Indonesia untuk lebih aktif menerjemahkan deklarasi itu ke dalam instrumen regional yang dapat mencegah dan mengatur TPPO. Sebagai sebuah industri, tindak kejahatan ini terus berkembang, terutama dalam pemanfaatan teknologi.
“Ini bukan industri yang stagnan, tetapi terus berubah, beradaptasi dengan pasar dan seterusnya, yang kadang-kadang pemerintah itu kalah cepat dengan aktivitas ini,” kata dia mengingatkan.
Aktor yang terlibat juga beragam, tidak terkecuali aparat pemerintahan. Aktor yang mendukung juga berkembang, mulai dari bankir, pebisnis, akuntan, hingga pengacara.
ASEAN Butuh Gugus Kerja
Dihubungi terpisah, Gabriel Goa dari Tim Lobi dan Advokasi, lembaga Zero Human Trafficking Network juga menyambut baik Deklarasi ASEAN untuk pemberantasan TPPO. Namun, dia meminta ada langkah konkret dari komitmen tersebut.
“Salah satu langkah yang harus diambil, adalah pembentukan task forceASEAN untuk perlindungan pekerja migran, pencegahan dan penanganan human trafficking,” ujarnya kepada VOA.
Gabriel menggarisbawahi langkah ini penting, karena perdagangan manusia adalah kejahatan luar biasa dan lintas negara.
Ada sejumlah langkah taktis yang direkomendasikan Gabriel. Pertama adalah penindakan yang lebih tegas bagi aktor intelektual, dan bukan hanya operator lapangan. Aktor intelektual, bisa saja berada di negara yang berbeda, dengan peristiwa perdagangan manusia itu sendiri. Karena itu, kerja ASEAN harus meliputi penindakan kepada aktor utama, di negara di mana dia memimpin operasinya.
Kedua, adalah perlindungan terhadap korban dan kesempatan sebagai justice collaborator bagi pelaku lapangan. Menempatkan pelaku lapangan yang ditangkap sebagai justice collaborator penting agar mereka mau dan mampu mengungkap dalang di balik jaringan yang ada.
“Kerja sama ASEAN sangat dibutuhkan, tidak hanya di mulut tapi juga harus mewujud nyata di dalam aksi konkret. Kalau berhasil, ASEAN bisa menjadi pilot program,” tambah Gabriel.
Langkah konkret ketiga adalah melindungi korban perdagangan orang, yang saat ini sudah berada di negara-negara tujuan. Misalnya, korban TPPO asal Indonesia yang kini berada di Malaysia sebagai pekerja ilegal harus diberi kesempatan untuk mengurus dokumen secara prosedural. Tujuannya adalah agar para korban ini menjadi pekerja legal di negara tujuan.
“Supaya mereka bisa memperoleh pemenuhan atas berbagai hak, seperti kesehatan, hak pendidikan, juga hak atas mata pencaharian wajar,” tambahnya.
Tak Semua Deklarasi Berlanjut
Dalam diskusi FMB 9, pembicara yang lain, Rolliansyah Soemirat, Direktur Polkam ASEAN, Kementerian Luar Negeri mengakui sudah ada banyak komitmen tingkat ASEAN yang perlu diikuti oleh aturan turunan, baik di tingkat nasional maupun regional.
“Misalnya, kalau kita bicara masalah perdagangan orang, TPPO, itukan sebenarnya ASEAN sendiri sudah punya konvensi ACTIP, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons dari 2015. Itu sudah ada turunannya, work plan di tingkat regional, kerja sama penanganan trafficking in persons,” kata Rolliansyah.
Karena itu, Rolliansyah menyebut bahwa deklarasi adalah satu hal, dan upaya kolektif ASEAN untuk menurunkannya dalam tataran praktik, adalah hal yang berbeda.
Dia juga mengakui, bahwa jika Indonesia harus menuntut negara anggota ASEAN untuk berbenah dalam isu ini, maka pekerjaan rumah di dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Kita akan mendorong negara-negara lain untuk mengedepankan political will-nya, untuk mengimplementasikan semua deklarasi, konvensi, keputusan, yang sudah ada sebelumnya,” lanjut Rolliansyah.
Dalam kasus Deklarasi Cebu untuk perlindungan pekerja migran, misalnya, Rolliansyah menyebut bahwa kesepakatan itu sudah turun dalam bentuk konsensus di ASEAN. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut agar deklarasi terwujud dalam ASEAN Convention karena gagal disepakati dalam beberapa isu.
“Tapi, paling tidak ada ASEAN Consensus tentang perlindungan pekerja migran,” lanjut Rolliansyah.
Korban TPPO Berpendidikan
Benny Rhamdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mengakui ada perubahan dari kejahatan TPPO, misalnya terkait korban dari dalam negeri.
“Menarik misalnya, hari ini ya secara mutakhir, yang menjadi korban bukan lagi mereka yang dikategorikan berpendidikan rendah, atau mereka yang tidak memiliki akses informasi,” kata Benny.
Dia memberi contoh, dalam kasus TPPO di Kamboja dan Myanmar terakhir ini, korban rata-rata berpendidikan sarjana S1 dan D3.
“Dan mereka tahu persis, bahwa keberangkatan mereka tidak resmi. Tapi karena iming-iming bekerja dengan cara cepat, semua keberangkatan dibiayai dan gaji tinggi,” lanjutnya.
Karena semakin kompleksnya persoalan, Benny berharap Deklarasi ASEAN ini memperkuat semangat dan komitmen kawasan. Indonesia, kata dia, bisa menggunakan forum-forum diplomatik untuk bersikap keras kepada Malaysia, Kamboja atau Myanmar agar tidak ada negosiasi dan kompromi terhadap TPPO.
Di dalam negeri, Benny meyakinkan bahwa upaya pencegahan sudah dilakukan, misalnya dengan Undang-Undang 18/2017. Di pasal 8 ayat 1, ada perlindungan administratif dan teknis untuk mencegah TPPO. Misalnya dengan ketentuan bahwa setiap pekerja migran harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga memiliki sertifikasi kompetensi. Selain itu, penggunaan visa kerja juga menjadi syarat.
“Modus yang digunakan oleh mereka yang berangkat ilegal itu pasti bukan visa kerja, tapi visa turis misalnya. Kemudian visa umroh dan ziarah untuk negara-negara Timur Tengah,” ujarnya.
Menurut data BPPMI, ada 1.324.102 pekerja migran Indonesia di Malaysia, yang bekerja di sektor perkebunan, operator dan pekerja domestik. Di Singapura ada kurang lebih 322.000 pekerja, terutama di sektor konstruksi. Sedangkan di Thailand ada 4.000 pekerja konstruksi dan pelaut, di Brunei ada 92.000 untuk pekerja domestik dan general worker, sedangkan di Myanmar ada 1.016 orang.
Source: VOA